
MAKAM PALSU TIDAK SELALU NEGATIF
Catatan Henri Nurcahyo
Belakangan ini sedang ramai perihal sejumlah makam palsu di Ngawi dan Mojokerto dibongkar warga. Pembongkaran dilakukan karena makam-makam tersebut dianggap palsu dan mengaburkan sejarah leluhur serta dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir orang. Konon makam tersebut ada yang sengaja dibuat berdasarkan mimpi atau mendapatkan petunjuk atau narasumber dari sejumlah kiai.
Sebenarnya masih banyak makam palsu yang patut juga dipertanyakan. Sebut saja satu contoh, Situs Siti Inggil di Kabupaten Mojokerto menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa, dipercaya sebagai makam pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, Raden Wijaya. Sementara pendharmaan Raden Wijaya juga dipercaya berada di Candi Simping, Blitar. Jadi, mana yang benar? Apakah Raden Wijaya sudah menjadi mualaf sehingga dimakamkan secara Islam? Kalau toh yang di Trowulan itu makam palsu, mengapa tidak dibongkar sekalian?
Hampir setiap desa memiliki makam yang dipercaya sebagai makam dari orang yang mbabat alas atau cikal bakal berdirinya desa tersebut. Di Kumitir Mojokerto, di mana terjadi pembongkaran makam palsu tersebut, masyarakat setempat percaya bahwa dua makam yang asli hanyalah makam Mbah Sagu dan Mbah Budiman, yang dipercaya sebagai leluhur Dusun Bendo. Di Bungurasih, Sidoarjo, juga ada makam Mbah Bongoh dan Mbah Bungur, yang (semula) diyakini sebagai orang yang berjasa mendirikan desa Bungurasih. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah membuktikannya? Apakah cukup hanya berpegang pada cerita rakyat yang berkembang di masyarakat selama ini?

Bagaimanapun keberadaan sebuah makam kuno seringkali menimbulkan berbagai penafsiran. Tafsir yang pertama, makam tersebut memang betul-betul sebuah makam (kuburan) seorang tokoh yang dapat dilacak sumbernya secara meyakinkan. Nama dan waktu meninggalnya bisa ditelusuri secara jelas. Biasanya makam yang seperti ini ada di lingkungan pesantren atau lahan tertentu yang jelas kepemilikannya.
Kedua, bisa jadi ada kerancuan antara sebutan makam dengan maqom. Kalau makam adalah kuburan maka maqom adalah tempat berpijak, atau dalam bahasa Jawa disebut petilasan. Sebagai contoh, kerancuan inilah yang menyebabkan seolah-olah makam Syekh Jumadil Kubro ada di mana-mana. Ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo, mubaligh terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim ada di beberapa tempat, yaitu Trowulan Mojokerto, Semarang, hingga di lereng gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan.
Menurut KH Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal dengan nama Gus Baha, makam Syekh Jumadil Kubro yang betul adalah di Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini karena Syekh Jumadil Kubro adalah seorang wali, kakek dari Sunan Ampel, ketua Walisongo. Sunan Ampel memiliki ayah bersama Mbah Ibrahim Asmaraqondhi, yang berasal dari Cempo, di Thailand atau Kamboja. Cempo, merupakan tempat kelahiran Sunan Ampel dan kemudian ikut orang tuanya ke Tuban, sebagai kota pelabuhan waktu itu. Gus Baha mengatakan, Ibrahim Asmaraqondhi, ayah Sunan Ampel itu tinggal di desa dekat rumah orang tuanya di Tuban. Dikatakan, bapaknya Ibrahim Asmoroqondhi, Syekh Jumadil Kubro, itu orang alim, maka dia ke Mojokerto. Karena wali, syafaatnya ikut nabi di pusat kota.
“Karena dulu pusat kota Mojokerto, pusat kota Nusantara, ada kerajaan Majapahit. Secara logika masuk akal, Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota,” katanya.
Ketiga, bisa jadi keberadaan sebuah makam kuno yang tidak diketahui asal-usulnya lantas dibuatkan cerita perihal jatidiri dan silsilahnya dengan mencantolkan dalam sejarah yang sudah ada. Cerita tersebut lantas menyebut-nyebut sumber literatur yang sulit dibuktikan kesahihannya. Apalagi lantas mengarang cerita berdasarkan “penerawangan” alias menggunakan cara-cara spiritual. Tentu saja dalam konteks sejarah hal ini sulit dipertanggungjawabkan. Mengutip istilah Soenarto Timoer, bahwa hal ini tergolong dalam apa yang disebut “Dongeng yang Disejarahkan.” Artinya cerita tentang makam tersebut adalah dongeng (fiksi) namun sengaja dicarikan cantolannya dalam sejarah (fakta).
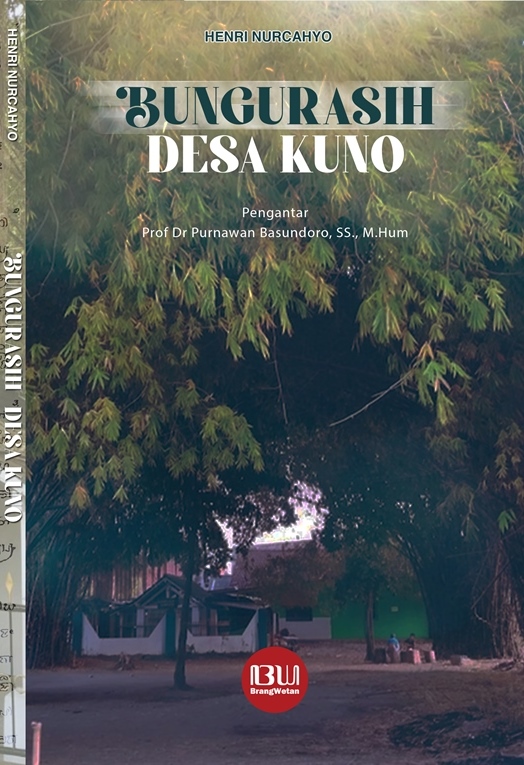
Keempat, apa yang disebut sebagai makam itu sesungguhnya hanya gundukan tanah biasa. Sengaja disebut makam dan dikeramatkan demi tujuan tertentu. Misalnya, ada makam yang sengaja dibangun di dekat sebuah situs purbakala berupa bebatuan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Tujuannya agar orang tidak merusak situs tersebut lantaran “takut” dengan adanya makam keramat. Itulah sebabnya sering ditemukan adanya “nisan-nisan palsu” atau nisan tanpa makam di areal pemakaman lantaran itu memang bukan nisan melainkan artefak purbakala. Supaya artefak itu tidak diganggu maka di tempat itu sengaja dijadikan lahan pemakaman.
Motivasi yang sama juga dilakukan untuk tujuan konservasi pohon beringin yang memiliki fungsi penjaga mata air. Karena pohon beringin memiliki kemampuan menyimpan air sehingga tidak pernah kering kerontang meski musim kemarau yang panas sekalipun. Biasanya di dekat tempat tumbuhnya pohon beringin ini terdapat mata air. Nah agar orang tidak merusak atau apalagi menebang pohon beringin tersebut maka dibuatlah sebuah makam di dekatnya. Bahkan ada yang dibuat sebuah punden, diberi pagar, dan dijadikan lokasi untuk ritual dengan aneka perlengkapan berupa bunga-bunga dan dupa. Sepintas hal ini terlihat sebagai perbuatan syirik, padahal itu adalah sebuah kearifan lokal untuk menjaga atau konservasi pohon beringin yang punya banyak manfaat secara ekologis. Lebih dari itu, maka keberadaan punden tersebut lantas diikuti dengan sebuah cerita perihal tokoh yang mbabat alas desa tersebut. Namanya misalnya Mbah Sangkil, seorang punggawa kerajaan, atau salah satu pasukan Pangeran Diponegoro, atau bisa juga disebut-sebut sebagai keturunan wali atau ulama.
Jadi, terkait dengan hal ini, apakah yang selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu makam dari seseorang (tokoh benar-benar sebuah fakta sejarah ataukah hanya fiksi? Ini memang masalah penafsiran. Jangankan yang berupa cerita rakyat, yang namanya sejarah itu sendiri sebetulnya juga sebuah penafsiran. Karena sejarah bukanlah sebuah rekonstruksi fakta. Bisa jadi penafsiran itu akan berubah dengan ditemukannya bukti-bukti baru yang melengkapi penafsiran sebelumnya atau bahkan menyanggahnya.
Contoh yang populer adalah perihal wajah Gadjah Mada. Ketika seorang Mohamamad Yamin mempublikasikan wajah Gadjah Mada banyak yang menentangnya. Mereka menganggap wajah tersebut hanyalah wajah dari sebuah keramik kuno zaman Majapahit. Bahkan ada yang menghubung-hubungkan dengan wajah Yamin sendiri. Menanggapi berbagai tudingan ini dengan san-tainya Yamin berkilah, “Kalau ini bukan Gadjah Mada, tunjukkan mana yang sesungguhnya.”
Wajah Gadjah Mada versi sejarawan Moh Yamin itulah yang kemudian dipajang di mana-mana bahkan dibuat dalam bentuk patung. Hingga kemudian sejarawan dan juga arkeolog Agus Aris Munandar mempublikasikan wajah Gadjah Mada dalam versi lainnya. Gadjah Mada versi Agus ini juga dibuat dalam bentuk patung di sejumlah tempat. Meski ternyata wajah Gadjah Mada yang satu ini mirip dengan sosok Bima dalam pewayangan.
Karena itulah, biarkan saja cerita-cerita berkembang perihal jatidiri dan asal-usul makam di suatu desa. Kesemuanya itu adalah rekaman memori kolektif masyarakat lokal dalam hal menafsirkan asal usul desanya selama belum ada fakta baru yang dapat menyempurnakannya.
Sebagai cerita rakyat, biarlah berbagai versi berkembang dengan penafsiran yang berbeda-beda. Sulit membuktikan mana yang benar. Bagaimanapun yang namanya cerita rakyat adalah sebuah bentuk tradisi lisan yang dituturkan secara turun temurun secara lisan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Sangat mungkin terjadi pembelokan cerita atau bahkan memunculkan versi yang lain lagi.
Perihal makam Mbah Bungur dan Mbah Bongoh, saya sudah membahasnya panjang lebar dalam buku “Bungurasih Desa Kuno”. Dan ternyata, disebut desa Bungurasih bukan karena didirikan oleh Mbah Bungur, malah sebaliknya. Dia dinamakan Mbah Bungur (dan Mbah Bongoh) karena tinggal di desa Bungur. Artinya, desa Bungur sudah ada lebih dulu ketimbang Mbah Bungur itu sendiri. Sudah lazim ada tokoh yang diberi nama atau gelar sebagaimana nama daerah tinggalnya.

Karena ternyata, desa Bungurasih itu sudah ada sejak abad ke-9, tepatnya tahun 860 Masehi, ketika Raja Rakai Kayuwangi dari Mataram Kuno memberikan hak menjadi desa Sima dengan kewajiban menjaga bangunan suci bernama Kancana. Dan itu tercatat dengan jelas di Prasasti Gedangan atau disebut juga Prasasti Kancana, atau juga Prasasti Bungur, bahkan tercantum tanggalnya 31 Oktober 860 M.
Selengkapnya baca buku saya yaa…
Ringkasan ceritanya ada di sini: https://brangwetan.com/?p=2223
Atau datang langsung dalam acara Bedah Buku “Bungurasih Desa Kuno”, Minggu, 26 Januari 2025, pukul 09.00 WIB, di aula Dekesda, Jalan Erlangga 67, Celep, Sidoarjo. (hnr)
Catatan Henri Nurcahyo Belakangan ini sedang ramai perihal sejumlah makam palsu di Ngawi dan Mojokerto dibongkar warga. Pembongkaran dilakukan karena makam-makam tersebut dianggap palsu dan mengaburkan sejarah leluhur serta dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir orang. Konon makam tersebut ada yang sengaja dibuat berdasarkan mimpi atau mendapatkan petunjuk atau narasumber dari sejumlah kiai. Sebenarnya masih banyak makam…